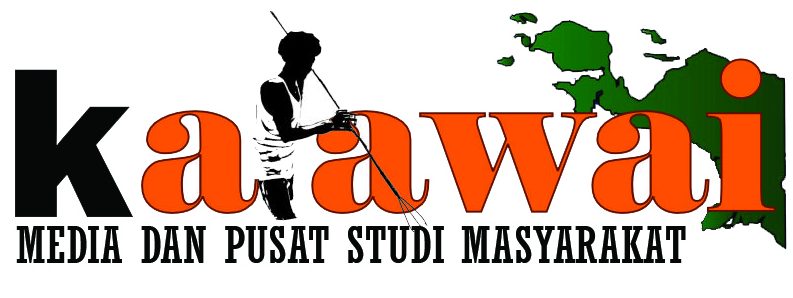Saya menguraikan materi saya ke dalam tulisan ini. Materi berbentuk power point berjudul Gerakan Sosial & Pengorganisasian Masyarakat. Presentasi tersebut untuk memantik diskusi sehari bersama kawan-kawan muda peserta pelatihan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) dari berbagai daerah di Papua yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Avaa di Kota Sorong, 26 Agustus 2024. Avaa sendiri adalah organisasi non pemerintah (0rnop/NGO) untuk pemberdayaan petani di Sorong. Walau terhitung baru Ornop ini mendampingi dan memberdayakan cukup banyak komunitas petani tradisional dan agrokultur di Sorong Raya.
Bagian saya menjadi satu tema tersendiri dari materi Pendidikan HAM selama sebulan penyelenggaraannya. Durasi seharian cukup bagi kami untuk saling bertukar pandangan dan pengalaman selama sesi. Sesi berakhir dengan pemutaran dua film dokumenter yang diproduksi kalawai.org di Merauke yang menggambarkan tentang komunitas buruh harian bongkar muat “Doji” dan masyarakat adat “Bapa Bon dari Zenegi”.
Apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman semata, baik dan buruk kerja pengorganisasian selama ini, dengan dukungan bacaan terkait. Seperti Catatan Pengalaman Belajar Praktek Pengorganisasian Masyarakat di simpul belajar (2001), Gerakan Sosial Wacana Civil Society Bagi Demokrasi (LP3ES 2006), Menuju Gerakan Sosial Baru (insist press), dan bacaan lain yang relevan.
Apa itu Gerakan Sosial?
Beberapa kawan peserta mengatakan pendapat mereka tentang apa itu “gerakan sosial”. Pendapat itu tentu berdasarkan pengalaman pribadi mereka dari komunitas dan organisasi gerakan masing-masing. Seperti aktivis mahasiswa, aktivis petani, dan sukarelawan beberapa Ornop di Sorong Raya.
Pendapat mereka mendekati defenisi menurut Iwan Gardono, yang mengatakan gerakan sosial yang berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok civil society dalam mendukung atau menetang perubahan social ( Iwan Gardono Sujatmiko, dalam Gerakan Sosial). Atau menurut M. Diani dan I Bison di publikasi di Universitas Trento, 2004, bahwa gerakan sosial adalah sebentuk aksi kolektif dengan orientasi yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye bersama.
Ada lagi menurut Habermas, Offe, Melucci, dalam canel 1997 Gerakan sosial adalah “ruang antara” yang menjembatani civil society dan negara. Melalui ruang tersebut gerakan sosial mampu mempolitisasi civil society tanpa harus memproduksi control, regulasi, dan intervensi seperti yang dilakukan negara.
Gampangnya gerakan sosial adalah bentuk gerakan (aksi) untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Gerakan sosial sebenarnya adalah aksi protes kepada penguasa karena dianggap tiap tindakanya akan merugikan banyak orang.
Seperti pendapat para penulis yang dikutip dalam buku-buku di atas dan pendapat kawan-kawan ini, tentu bisa menjadi pendapat alternatif dari berbagai pendapat tentang gerakan sosial karena berdasarkan pengalaman masing-masing di tiap organisasi dan komunitas.
Gerakan sosial juga memiliki banyak julukan, baik oleh penguasa, ilmuan sosial, maupun oleh aktor-aktor gerakan sosial itu sendiri. Kita sering dengar sebagai berikut; kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (pressure group), agen control social (agen social controle), dan infrastruktur politik, dan lainnya.
Sedangkan untuk mengindetifikasikan aktor-aktor dalam gerakan sosial itu juga memiliki banyak rupa. Paling dominan gerakan sosial selalu diidentikan dengan satu kelompok yakni organisasi non pemerintahan (ornop/NGO). Di banyak negara ornop-ornop memainkan peran sentral dari gerakan sosial termasuk Indonesia, ini juga menyangkut dengan kerja-kerja mereka yang programatik, memberdayakan, hingga melakukan advokasi untuk kasus-kasus tertentu.
Tetapi apakah kemudian gerakan sosial hanya terbatas pada Ornop seperti pemahaman selama ini? Tentu saja tidak, gerakan sosial digerakan banyak aktor. Diantaranya, Ornop/ NGO, Ormas-ormas, organisasi komunitas, organisasi profesi, Partai politik, Media/Pers, dan lembaga Pendidikan termasuk didalamnya adalah gerakan mahasiswa itu sendiri.
Sejarah NGO sendiri bahkan tidak lebih tua dari sejarah peran partai politik (non electoral), peran media massa, sejarah gerakan mahasiswa, organisasi buruh, dan sebagainya. Gerakan dengan pelopornya NGO bahkan dianggap gerakan sosial baru (GSB) bukan gerakan sosial klasik/lama (GSK).
Dari aktor-aktor di atas digolongkan ke dalam tipologi berikut, terutama saat kita melihat aksi-aksi hari ini. Seperti aksi dan kampanye stop jual tanah, dilarang buang sampah, sahkan RUU Masyarakat Adat, Selamatkan bumi, revolusi, dan Papua merdeka dan masih banyak lagi.
Menurut David Alberle dalam Iwan g. Sujatmiko:2006 ada empat tipologi. Pertama, Arternative Movements ( mencoba mengubah Sebagian perilaku orang, seperti tidak merokok, tidak buang sampah sembarangan, dll). Kedua, Redemptive Movements (mencoba mengubah perilaku orang secara menyeluruh, seperti pada bidang keagamaan).Ketiga, Revormative Movements (Mencoba mengubah masyarakat namun dengan lingkup terbatas, seperti Gerakan persamaan hak kaum perempuan. Keempat Tranformative Movements (Gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh, seperti Gerakan-Gerakan komunis, dan Gerakan sejenisnya).
Fase Pada Gerakan Sosial
Seperti yang disinggung pada paragraf di atas tentang gerakan sosial baru (GSB) dan gerakan sosial klasik (GSK). Menurut Rajendra Singh Profesor Departeen of Social Work, Universitas Delhi dalam kumpulan tulisan Teori-teori Gerakan sosial baru[1]. Keduanya memiliki sejarah yang sama yaitu di mulai dari Eropa dan Amerika serikat. Bedahnya, GSK adalah gerakan sosial sebelum tahun 1920 an dimana gerakan ini cenderung sebagai gerakan ideologis dengan pendekatan marxisme leninisme. Slogan-slogan GSK seperti; revolusi, anti kolonialis, anti kapitalis, yang bercirikan marxisme yakni di gerakan oleh kelas social seperti kaum buruh.
Sedang GSB adalah gerakan sosial yang jauh berbeda dengan GSK karena tidak ideologis, bahkan tidak mau memposisikan diri sebagai gerakan kiri atau gerakan kanan. Gerakan yang dimulai sekitar 1920-1930 di Eropa dan Amerika ini menjadi semakin populer ketika Mahatma Gandhi tampil dengan gerakan tanpa kekerasannya dan menuntut kemerdekaan India dari Inggris.
GSB dikenalkan juga sebagai “Gerakan radikal yang membatasi diri”, karena cenderung hanya ingin menata kembali hubungan negara dengan masyarakat dan perekonomian. Juga tidak membatasi pada manusia saja, tetapi alam dan planet ini, maka ada slogan seperti selamatkan mama planet, ada lagi isu perubahan iklim, pelucutan senjata, anti nuklir bahkan rasisme. Contoh GSB hari ini seperti gerakan sabuk hijau di Kenya, gerakan masyarakat adat, hingga gerakan anti korupsi, gerakan lingkungan dan sebagainya.
Kedua fase memiliki perbedan yang jauh, tidak dimaksudkan untuk periodesisasi waktu tetapi lebih kepada ciri dan karakteristik dari gerakan sosial itu sendiri. Tidak juga ingin menunjukan mana yang lebih baik dan efektif dalam perjuangannya. Karena hal tersebut menyangkut kemampuan para pelaku gerakan sosial itu mengkontekstuasasikan metode agar lebih mendekati tujuan politiknya.
Dalam sumber lain dapat kita tangkap adalah terdapat gerakan neoklasik, gerakan ciri cenderung lebih kepada Gerakan neo marxis yang tidak lagi dibatas kepada partai komunis internasional sebagai sebuah syarat umum dari gerakan revolusioner. Kita bisa sebutkan gerakan ini sebagai Sosialisme abad 21. Marxisme menjembatani gerakan perlawanan baik kelas-kelas buruh maupun entitas lain seperti masyarakat adat, gerakan lingkungan. Sekaligus menjawab kritik dan tantangan GSB terhadap GSK itu sendiri.
Transformasi Gerakan Sosial di Papua
Kemunculan gerakan sosial di Papua tidak terlepas dari akar sejarah penindasan yaitu kepitalisme dan kolonialisme. Akar penindasan yang kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai persoalan multidimensional. Ada pelanggaran HAM, diskriminasi, marjinalisasi dan rasisme, depopulasi penduduk asli, perampasan lahan masyarakat adat, konflik bersenjata dan pengungsian, hingga premordialisme dan perpecahan orang Papua setelah Otsus dan banyak pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Lembagai Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau kini menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Papua Road Map mengklasifikasikan sebagai Pelanggaran HAM, Diskriminasi dan marjinalisasi, Kemiskinan, dan Persoalan politik masa lalu yang belu selesai.
Bentuk gerakan sosial di Papua selama 60 tahun ini adalah Gerakan sipil yang digerakan oleh berbagai organisasi gerakan sipil dalam dan luar negri, Gerakan mahasiswa di seluruh Tanah Papua dan Indonesia. Adalah juga gerakan bersenjata, awalnya di motori oleh bekas polisi Belanda (KNIL) kemudian mendorong penyerangan markas TNI di Arfai Manokwari 1965, selanjutnya ada deklarasi negara Republik Papua Barat 1 Juli 1971 oleh Zet Roemkorem dan kawan-kawan, yang juga membentuk sayap militer Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB).
Kini gerakan sosial di Papua memiliki cenderung dinamis, di samping dinamika internal gerakan nasional kemerdekaan yang tinggi karena konflik berbagai faksi politiknya. Memakai kalimat Benedic Anderson (1986) dalam Imagined Communities, kelompok muda gerakan nasionalis Papua memang suka bertengkar, atau Inu Kencana Syafii, budaya politik orang Papua[2], bahwa konflik biasanya karena beragam suku bangsa di Papua dan tiap-tiap suku ingin menunjukan eksistensinya.
Dengan segala bentuk penindasan dalam bahasa “pembangunan” Indonesia kemudian menciptakan realitas social politik baru sehingga memaksa generasi hari ini untuk tidak melihat gerakan sosial di Papua secara hitam dan putih. Seperti entitas Papua vs Indonesia, namun dengan perspektif kelas tertindas vs kapitalisme dan kolonialisme.
**
Pada akhir sesi diskusi, saya menegaskan pentingnya pekerjaan pengorganisasian masyarakat di basis-basis yang bukan saja tidak populer selama ini, tetapi juga melawan propaganda-propaganda yang mengurangi semangat kerja kawan-kawan muda di Papua.
Referensi:
- Trobowo, Darmawan dkk (2006), Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokrasi, LP3ES
- Kencana, Syafii (2017), Ilmu Pemerintaha, Bumi Aksara
- Soetomo (2013), Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya, Pustaka Pelajar.
- Wacana: Menuju Gerakan Sosial Baru, Insist Press
- Catatan Pengalaman Belajar: Praktek Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar
- Gerakan Sabuk Hijau: Wancari Maathai, peraih Nobel Perdamaian (2006), Marjin Kiri
[1] Buku Wacana Terbitan Incist Press berjudul Menuju Gerakan social baru
[2] dalam bukunya Ilmu Pemerintahan