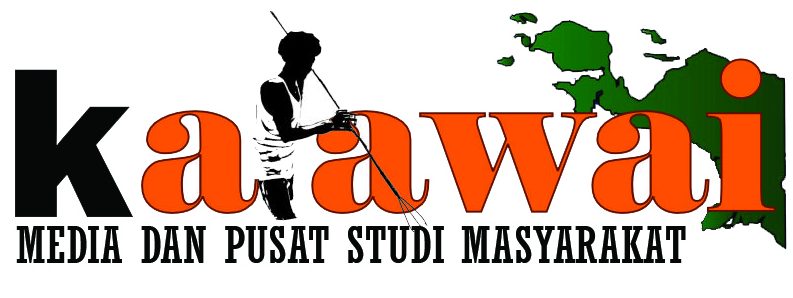Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melaksanakan program transmigrasi ke Papua. Melalui Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara Mentri Transmigrasi mengatakan proyek transmigrasi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo ini mampu meningkatkan kesejahteraan orang Papua. Walau kemudian di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRR RI) pada 29 Oktober 2024 Iftitah kembali menjelaskan tranmigrasi yang dia maksudkan. “Jangan di artikan secara sempit, bahwa transmigrasi selalu berasal dari luar Papua, akan tetepi berfokus kepada transmigrasi lokal dari daerah Papua lain ke daerah Papua tertentu dengan pertimbangan tertentu.” Setelah pernyataan itu, sepertinya isu tersebut berhasil diminimalisir agar tidak lagi dibahas secara luas.
Apakah tranmigrasi dari luar Papua itu bisa benar-benar dihentikan. Mari kita melihat sejarah dan sejauh mana pemerintah menjalankan program transmigrasi serta bagaimana strategi pemerintah menjalankan migrasi di luar program transmigrasi tersebut. Dengan tulisan ini saya berharap memberikan informasi di tengah wacana transmigrasi pemerintahan Prabowo Subianto. Terutama adanya kemungkinan migrasi penduduk ke Papua akan dengan atau tanpa transmigrasi. Ini adalah sesuatu yang mustahil dicegah karena sejalan dengan perluasan investasi di seluruh tanah Papua.
Transmigrasi, Sejarah dan Dampaknya Bagi Penduduk Papua[1]
Transmigrasi ke Papua dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda. Dimana untuk pertama kali Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke pada 21 Februari 1902. Kemudian tahun 1908 Belanda kembali menambah kuota penduduk dari Jawa untuk menempati wilayah Kuprik, Merauke. Selain Jawa, warga dari Pulau Rote juga di datangkan dan tinggal di kawasan yang kini mereka sebut Kampung Timor, Merauke. Setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, program transmigrasi dimasukan Soeharto ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Jumlah keluarga yang menjadi transmigrasi pada REPELITA ketiga III sejak 1979 hingga 1984 diseluruh Tanah Papua adalah 19.324 jiwa[1].
Masih dari sumber yang sama, target keluarga yang ikut REPELITA ke IV dari tahun 1985-1987 berjumlah 26.256 jiwa. Sehingga total penduduk transmigran ke Papua berjumlah 45.580 jiwa. Artinya sejak transmigrasi 1979-2000 ke Papua, sebanyak 78.650 KK (306.447 jiwa) dalam 270 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) tersebar diseluruh Papua, termasuk yang saat ini telah menjadi Provinsi Papua Barat[2]. Penempatan transmigrasi terakhir di Papua dilakukan pada periode tahun 1999-2000 sebanyak 650 KK, atau 2.884 jiwa, yaitu antara lain Babo (Teluk Bintuni) sebanyak 200 KK (910 jiwa), di Keerom (Arso 14) 100 KK (421 jiwa), di Merauke (Muting 10) 100 KK (499 jiwa), di SP 13 Mimika Kampung Bintuka 250 KK (1.054 jiwa).
Berbeda dengan transmigrasi Belanda yang relatif terbatas hanya untuk memenuhi tenaga kerja administrasi dan pendidikan, transmigrasi Indonesia sejak awal sudah dicurigai bermotif politik. Terutama karena tidak melalui konsultasi dengan pemerintah daerah Papua agar mengambil langkah lebih strategis yang tidak merugikan masyarakat adat Papua maupun negara secara umum. Menurut Theodor Rathgeber dalam esai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Kerangka Hukum dan Politik Untuk Dialog mengatakan bahwa program transmigrasi ke Papua dimaksudkan untuk memperkuat control administrasi dan politik di Papua. Menurutnya di tahun 1960 penduduk pendatang di Papua hanya 2,5 % dari total penduduk saat itu 736.700 orang. Selanjutnya di tahun 2003 angka tersebut meningkat menjadi 35 % dari total populasi 2, 387 juta orang[3].
Serupa dengan pernyataan itu, Max Auparay[4] mengatakan bahwa program transmigrasi adalah kebijakan pemerintah secara sistematis yang memaksakan pemerintah daerah untuk tidak memiliki pilihan lain dan harus melaksanakannya, karena ini kepentingan pemerintah pusat dengan menekan masyarakat Papua mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendaki tanpa pertimbangan kondisi sosial budaya sebenarnya[5].
Sejak awal terlihat pemerintah Soeharto memobilisasi penduduk ini sebagai upaya invansi sipil ke Papua terutama karena penduduk yang di mobilisasi adalah penduduk dari Pulau Jawa dalam jumlah besar. Perubahan pola transmigrasi baru terjadi ketika pemerintah Indonesia terus-menerus mendapat kritik dari organisasi sipil dunia. Puncaknya ketika Ny. Eegje School Mentri Pembangunan Koperasi Belanda sekaligus berkapasitas sebagai pimpinan Inter Govermental Group on Indonesia (IGGI) mengunjungi Papua, tepatnya ke Koya 1986[6] untuk memastikan sendiri berbagai surat yang dia terima dari negara Eropa Barat dan akhirnya meminta pemerintah Indonesia untuk menambah porsi migran lokal sebesar 20 % sampai 50 % agar razio masyarakat adat (Papua) dan non Papua seimbang[7]. Untuk menghindari tuduhan kolonisasi, pemerintah Indonesia merubah pola transmigrasi yang hanya berfokus dari pulau Jawa ke Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bahkan menambah porsi migran lokal Papua sendiri.
Sentralisasi politik dan pemerintahan memiliki konsekuensi yang besar pada berbagai bidang di Papua, terutama bidang sosial, ekonomi, ekologis dan budaya. Seperti pembukaan lahan-lahan transmigrasi di kawasan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat secara komunal oleh klan atau suku dan marga, yang diwariskan turun temurun.
Klaim-klaim pemerintah tentang pelepasan secara sah kebanyakan dibantah masyarakat adat yang merasa dimanipulasi dan diintimidasi. Kabupaten Keerom yang waktu itu masih masuk dalam wilayah administratif Jayapura juga menjadi target program transmigrasi hingga proyek-proyek perkebunan sawit, sebagaimana yang dikatakan Servo Tuamis bahwa pelepasan tanah seluas 50.000 Hektare di Arso Keerom dilakukan secara intimidatif dan penuh manipulasi karena beberapa tokoh yang seharusnya ikut menandatangani tidak berada di Arso tahun 1982, setelah pelepasan illegal itu kawasan tersebut kemudian kini menjadi perkebunan sawit dan sebagian menjadi pemukiman transmigrasi. Sejak itu sampai hari ini masyarakat adat Keerom masih berusaha memperjuangkan hak-hak atas tanah tersebut[8].
Siegrified Zollner dalam Esai berjudul Budaya Papua dalam Transisi: Ancaman Akibat Modernisasi-Jawasnisasi dan Diskriminasi[9] menyebutkan, ada seorang pemilik tanah yang buta huruf, dipinggir Sungai Mamberamo “dikondisikan” dengan beberapa botol bir untuk menandatangani dokumen yang isinya tidak ia pahami. Pada 1996, sebuah surat kontrak yang berisi penyerahan tanah seluas 50,000 hektare yang dibuat seorang perwirah tentara asal Batak harus dibatalkan. Pasalnya penduduk tidak mengetahui seberapa luas tanah tersebut. Pola-pola ini sangat umum diketahui dari masyarakat adat Papua, yang secara khusus berhadapan dengan transmigrasi dan investasi di Papua.
Masalah di bidang ekologis adalah deforestasi karena pembangunan pemukiman di kawasan hutan alam yang selama ini menjadi tempat mencari makan penduduk asli, seperti hutan sagu, lahan berkebun, berburuh hewan, juga merusak kawasan hutan sakral dan situs-situs budaya setempat. Deforestasi juga menjadikan kawasan pemukiman dan sekitarnya menjadi sarang nyamuk malaria yang memungkinkan menjadi penyebab kematian penduduk asli maupun migran[10]. Kepadatan penduduk yang tidak terkontrol juga mengakibatkan beberapa daerah terutama pusat-pusat kota menjadi padat penduduk, yang kemudian pemukiman terpaksa di bangun pada kawasan yang tidak seharusnya seperti gunung, kaki gunung maupun aliran sungai. Pada bidang sosial, kemiskinan menjadi persoalan tersendiri yang menjadi fokus pemerintah daerah yang notaben memiliki fokus kepada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat adat justru mengantisipasi lonjakan penduduk karena migrasi dan kemiskinan yang mengikuti.
Hingga reformasi dan berlakuknya Undang-undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001, laju transmigrasi tidak benar-benar dihentikan walaupn terjadi penolakan dari Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh rakyat Papua. Merujuk UU 21 Tahun 2001, Bab XXIII Tentang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pasal 61 poin 3 dan 4, penempatan penduduk di Provinsi Papua dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan pemerintah dilakukan berdasarkan persetujuan gubernur, penempatan penduduk itu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Faktanya, walau terkesan sunyi senyap mobilisasi penduduk transmigrasi tidak benar-benar berhenti, hanya tidak terpublikasikan. Di Kabupaten Keerom transmigrasi baru benar-benar berhenti pada tahun 2010[11].
Program ini lalu menimbulkan polemik dalam wacana heterogenitas, pluralitas dan identitas kebangsaan di Papua. Perubahan terus terjadi, dinamika sosial membawa arus program transmigrasi ini berubah menjadi migrasi penduduk;dari tranmigrasi yang digerakan pemerintah kepada migrasi penduduk secara spontan. Migrasi penduduk tidak lagi didorong janji-janji pemerintah seperti kesejahteraan, kepemilikan sekian hektar tanah namun migrasi kini secara suka rela, faktor utama di dorong oleh kehadiran berbagai perusahaan di Papua. Maka tidak heran setiap tahunnya data statistik Papua menunjukan peningkatan jumlah penduduk yang siknifikan. Penduduk yang masuk ini sudah dapat dipastikan adalah para pencari kerja yang ingin merubah nasib pada wilayah-wilayah investasi di Papua.
Tahun 2008 telah dikeluarkan peraturan daerah Provinsi (Perdasi) Papua No. 7 Tahun 2008 Tentang Pemukiman, dan Perdasi No. 15 Tahun 2008 Tentang Kependudukan, namun dipastikan tidak dapat membendung migrasi spontan yang terus masuk. Otsus sebagai “senjata” utama yang diharapkan secara ekplisit melindungi dan menjamin eksistensi Masyarakat Adat Papua, baik melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) nyatanya gagal, laju migrasi spontan tidak dapat dibendung. Ketidakmampuan UU Otsus Papua, ditambah dengan UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada akhirnya mempermudahkan penduduk migran untuk merubah status kependudukan secara suka rela. Mendapatkan status kependudukan adalah hak warga negara, dan menjadi syarat mutlak dalam mendapatkan akses berbagai pelayanan publik yang disediakan oleh negara, khususnya fasilitas Kesehatan, Pendidikan, transportasi dan lainnya. Sebaliknya di Papua, bahkan di Kota Jayapura Orang Asli Papua (OAP) masih kesulitan mengakses layanan ini sebab belum terdata dengan baik dan belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Berdasarkan fakta dan sejarah yang dipaparkan, ini sebuah ironi bagi Orang Asli Papua.
Tulisan ini tidak bertujuan untuk membatasi Hak Asasi Manusia warga negara lainnya, dengan mengangkat wacana transmigrasi dan migrasi di Papua. Namun untuk membuka diskursus yang lebih luas, mengajak semua pihak untuk mengkaji lebih jauh dampak pembangunan terhadap masyarakat adat. Khususnya diwilayah perkotaan dan atau masyarakat adat yang lokasinya dijadikan target pembangunan berserta sentral-sentral produksi, pusat pemerintahan, pendidikan, dan aktivitas layanan publik lainnya. Dampak pembangunan berserta konsekuensi yang diterima oleh masyarakat adat tidak hanya ditanggung oleh generasi sebelum yang melepas dan merelakan tanah adatnya untuk dijadikan hutan beton, tetapi generasi hari ini dan yang akan datang.
Dalam konteks hari ini wacana transmigrasi dan penolakan-penolakan yang terjadi sama sekali tidak akan mempengaruhi pertumbuhan pendudukan yang masuk ke Papua. Baik melalui program transmigrasi maupun melalui migrasi spontan pencari kerja tiap harinya. Migrasi spontan sering terjadi secara suka rela maupun mereka yang datang karena direkrut oleh para agen perusahan di kampung halaman mereka. Lemahnya elit pejabat birokrasi dan UU Otsus Papua menjadi faktor utama keleluasaan Jakarta mengatur Papua sesuka hari.
***
[1] Tulisan yang dipublikasi ini telah di edit setelah sebelumnya adalah bagian dari pembahasan penulis dalam penelitian tahun 2019 diselenggarakan Yayasan Dusun Anak Papua (Yadupa) berjudul Terhempas Dari Rumah Adat (Studi Kasus Orang Port Numbay di Tengah Perkembangan Kota Jayapura).
[1] Max Auparai hal 27, mengutip data DR. George Junus Aditjondro, 200:247
[2] Resistensi Papua Terhadap Program Transmigrasi, Siti Fatimah danAnharudin Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Kemenakertrans. Hal 62
[3] Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat, Studi Realitas Sosial dan Perspektif Politis, diterbitkan oleh The Evagelical Church in the Rhineland dan Gereja Kristen Injili di Papua
[4] Intelektual dan penulis yang berkerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)
[5] Max Auparay, Ekonomi Migrasi Penduduk di Papua, 2012; Hal 7
[6] Koya adalah salah satu kawasan di kota Jayapura masuk dalam wilayah DIstrik Muara Tami.
[7] Max Auparay, Ekonomi Politik Migrasi di Papua, 2012, Hal 21.
[8] Keterangan Servo Tuamis Ketua Dewan Adat Keerom saat di wawancarai penulis dalam riset ELSAM JAKARTA dengan Judul “Assesment Tentang Kondisi Masyarakat Adat Keerom yang Berstatus Sebagai Buruh Perkebunan Sawit di Kabupaten Keerom Papua” 2021.
[9] Esai tersebut dalam buku berjudul Hak-hak EKonimi, Sosial, dan Budaya di Papua Barat, diterbitkan pada Oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, 2006.
[10] Seperti yang terjadi pada awal-awal program ini, kematian 8 orang penduduk migran di Aimas Sorong tahun 1981, 18 transmigras di Arso dan prafi meninggal karena Malaria 1882, Kembali tahun 1984, 5 penduduk lembah kebar dekat transmigrasi prafi meninggal karena malaria.
[11] Wawancara penulis bersama kepala Disakertrans Keerom pada Januari 2022. Wawancara dengan judul penelitian adalah Assesment Tentang Kondisi Masyarakat Adat Keerom yang Berstatus Sebagai Buruh Perkebunan Sawit di Kabupaten Keerom Papua yang diselengarakan ELSAM Jakarta sejak 2020.