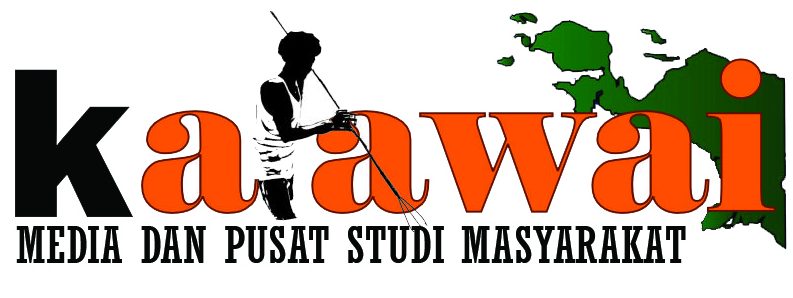Perampasan lahan, kemiskinan, diskriminasi, rasisme, serta pembunuhan warga sipil yang tiap waktu kita lihat dan bicarakan di Tanah Papua adalah bagian dari upaya proletarisasi. Kapitalisme berupaya memisahkan rakyat Papua dari corak produksinya, dengan pemisahan teknologi dan sistem pengetahuan sebagai sarana produksi dari entitas masyarakat adat sebagai produsen utama, yakni orang Papua dan tanah adat. Proses pemisahaan ini membuat luka, cucuran darah, membawah kematian ke dalam hidup para korbannya dalam arti harafia yang sebenarnya “serta penghancuran paripurna terhadap tatanan sosial tradisional” (Polanyi, dalam Mulyanto, 2012).
“penghancuran paripurna” ini terjadi hampir di seluruh dunia. Kolonial kapitalis memaksimalkan teknologi modern serta kekuatan militer ke wilayah-wilayah jauh, yang peradabannya lebih tua tapi sangat muda untuk ditaklukan. Tercatat pergerakan kolonialis modern untuk pertama kali di mulai oleh Spanyol abad ke 16 di Karibia dan Sebagian Amerika latin. Pergerakan ini di mulai dari kawasan Eropa ke daratan Hindia melalui rute barat. Rute ini kemudian membuka tambang perak di Peru dan Mexico. Melalui penjarahan ke wilayah baru yang tidak memiliki teknologi modern untuk mengelola sumber pangan dan energi mereka, sehingga menjadi keuntungan bagi kapitalis Eropa. Menurut Henry Bernstein (2020: 53) Inggris dan Belanda dua negara kecil Eropa bagian barat laut bergerak lebih cepat menuju kapitalisme agraria dan selanjutnya kapitalisme industri. Pergerakan Belanda itu tentu saja termasuk wilayah nusantara yang di kuasai oleh gurita kapitalis Belanda yaitu VOC (Verenigde Oost Indische Commpagnie).
Kisah klasik perkembangan kapitalisme ini adalah upaya proletarisasi yang menghancurkan tatanan sosial para petani tradisional di seluruh Eropa, kemudian menjadi ciri kapitalisme yang terbaca sampai sekarang. Mulai dari Inggris akhir abad ke 18 pengkaplingan dan penggusuran kaum petani terjadi secara cepat dan paripurna di abad 19. Masa ini disebutkan sebagai masa proletarisasi massal (Mulyanto. 2012: 28). Selain tercatat di mulai dari Inggris, Karl Marx mengatakan perkembangan kapitalisme ada juga Jalur Pruasia dan Amerika, dan juga Jalur Asia Timur (Berstein, 2020: 38). Masing-masing tempat ini memiliki ciri berbeda tergantung pada perkembangan masyarakatnya.
Kapitalisasi tanah di Inggris dilakukan berdasarkan berbagai perundangan-undangan yang melegitimasi proses pemisahaan petani dari tanah garapan mereka, antara lain ada bill of incloser of commons[1], ada Bill of Reform[2], dan berbagai peraturan teknis lainnya. Berbagai peraturan itu melegitimasi perampasan lahan yang mengakibatkan petani tidak lagi dapat memproduksi makanan mereka sendiri. Kedua, karena setelah tidak bisa lagi menghasilkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri, mereka juga tidak bisa dapat bantuan berbagai bentuk bantuan dan jaminan hidup tradisional (Mulyanto, 2021: 29). Targetnya adalah kapitalis mendapatkan tenaga kerja sangat murah, mempekerjakan orang dewasa perempuan, laki-laki bahkan juga anak-anak, dengan jam kerja yang mencapai 16 jam per hari. Kebiadaban ini kemudian menjadi role mode bagi para kapitalis Eropa hingga ke seluruh dunia.
Perjalanan kapitalisme ini menjadi malapetaka dalam sejarah penindasan manusia modern, karena menyebabkan kehancuran sistemik dalam tatanan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Terutama mengakibatkan munculnya klausal yang disebut sebagai pemiskinan dan penghancuran sumber produksi masyarakat; kausalitas yang memaksa mereka beralih menjadi buruh walau dengan upah sangat murah. Karena itu, proletarisasi diajukan sebagai suatu teori oleh Karl Marx disebutkan akumulasi primitif untuk menggagalkan teori akumulasi primitif Adam Smit yang menilai sesuatu secara ahistoris tetapi masih dianggap sebagai fondasi pemikiran kapitalisme waktu itu, bahkan sampai sekarang.
Akumulasi primitif Marx, di awali dengan kapital dan timbunan kekayaan kelas pemilik sarana produksi merupakan hasil perampasan terhadap kekayaan sosial hasil kerja golongan lain. Yang oleh Adam Smit dan para ekonom borjuis percaya bahwa keberadaan kelas-kelas sosial dalam masyarakat kapitalis tercipta secara suka rela dan damai di bawah pengawasan pasar yang adil (Mulyanto, 2012:44). Ini tentu sebagai akar perdebatan antara para marxis dengan para pemikir borjusi yang tidak berujung sampai sekarang. Para intelektual borjuis berpendapat bahwa kapitalisme tidak terelakan bagi negara-negara maju, sebaliknya sosialisme, marxisme-leninisme merupakan rintangan serius untuk menciptakan kemakmuran dan peradaban teknologi modern (Fukuyama, 2004:149). Pernyataan Fukuyama di awal 1990 ini adalah sedikit dari perdebatan panjang intelektual borjuis vs marxis dalam melihat baik buruk kapitalisme bagi umat manusia.
Petani, Masyarakat Adat dan kapitalisme Indonesia
Hari ini, petani dan masyarakat adat yang dipahami atau yang didefinisikan secara global tentu berbeda. Petani tradisional sebagai penggarap tanah antara lain petani kecil, petani skala kecil dan petani keluarga adalah yang maksudkan. Walaupun Henri Bertstein (2020) mengatakan bahwa sejak kira-kira 12.000 tahun yang lalu, sejumlah bentuk petani tetap telah menjadi fondasi material masyarakat. Perubahan agraris bisa ditemukan hingga sebagian besar masyarakat di Asia, wilayah tergarap di Afrika utara dan Eropa, dan di sebagian wilayah yang biasanya penduduknya jarang di Afrika Sub Sahara dan Benua Amerika. Lanjut Berstein, dalam masyarakat agraris mayoritas penggarap tanah adalah petani kecil.
Sebab itu sebagai masyarakat agraris masyarakat adat boleh dikatakan sebagai petani kecil atau petani keluarga yang menyediakan makan untuk kebutuhan sendiri (Subsisten). Namun karakteristik masyarakat adat dan petani berbeda, termasuk defenisi. Masyarakat adat adalah masyarakat tradisional dan asli, yang tatanan sosial budayanya belum dihancurkan oleh kapitalis, sebagaimana dimaksud Marx dalam sejarah perkembangan masyarakat awal atau purba, atau komunisme primitif dalam terjemahan inggris[3]. Sedang petani Eropa dan Jawa pada saat kemunculan kapitalis abad 18 dan 19 adalah masyarakat feodal yang penguasaan mayoritas tanah garapan ditentukan oleh tuan-tuan tanah dan kerajaan. Sementara masyarakat adat hidup secara kolektif pada komunitas suku dan masing-masing memiliki klaim penguasaan wilayah tanah dan laut yang luas[4].
Karena kapasitasnya itu, terutama kepemilikan atas tanah yang sangat luas, masyarakat adat dianggap sebagai penghambat utama kapitalisme. Banyak ahli berpendapat bahwa bersitahannya bentuk-bentuk produksi non kapitalis “petani kecil” menghabat perkembangan penuh kapitalisme, beberapa pengamat melihat hambatan ini sebagai kemajuan, karena semakin sedikit kapitalisme berarti semakin sedikit ketimpangan. Pengamat lain melihat hambatan ini sebagai kemunduran, karena menurut mereka bagaimana kapitalisme harus terwujud dulu secara penuh, barulah kita dapat meraih masa depan sosial (T. M. Li, 2020: 10).
Sekitar 350 juta masyarakat adat di dunia hari ini berada dalam kuasa negara modern, terutama pasca berakhir perang dunia ke II. Dimana nasionalisme kebangsaan negara-negara tersebut justru terbentuk bahkan tidak lebih dari 100 tahun yang lalu. Berbeda dengan masyarakat adat dalam kapasitas sebagai masyarakat pribumi atau masyarakat awal yang memiliki sejarah yang jauh lebih tua. Kuasa negara yang baru seumuran jagung ini, mengakibatkan masyarakat adat dan segala kekayaan dan kebudayaanya itu harus tunduk kepada hukum nasional yang berlaku, bahkan masyarakat adat membutuhkan legitimasi negara jika tidak mau dianggap illegal, karena menjalankan sistem hukum dan nilai sendiri.
Di Indonesia, posisi masyarakat adat dalam UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) letaknya berada di bawah negara. Dengan asumsi bahwa negara menjadi organisasi kekuasaan yang adil ( Elcid Li, 2021: 68). UUPA tahun 1960 tersebut mengakui masyarakat adat yang berdasarkan kriteria yang merupakan masyarakat adat (indigenous peoples) negara ini. Tetapi selain UUPA, Undang-undang No 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan dan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1970 tentang Hak penguasaan Hutan (HPH). Membatasai hak-hak masyarakat adat dan anggotanya untuk mengambil hasil hutan perlu ditertibkan ( R.E. Bosko, 2006: 73).
Inkonsistensi negara dalam menghormati posisi masyarakat adat ini dapat terbaca sebagai bagian dari upaya pelehaman ruang masyarakat adat itu sendiri. Terutama menyangkut dengan status negara di bawah bayang-bayang liberalisme dan neo liberalisme. Ketika Soeharto berhasil menggeser Soekarno dan atas nama kestabilan pangan nasional mengeluarkan beberapa undang-undang mendukung upaya kapitalisme di Indonesia, salah satunya Undang-undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA), dan melakukan banyak lobi kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga keuangan. Seperti mengerakan Adam Malik sebagai mentri luar negri untuk membangun kerja sama dengan negara-negara kreditur dan membentuk Internal Govermental Group on Indonesia (IGGI), para anggota terdiri dari Bank Pambangunan Asia (Asia Development Bank), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank), United Nation Development Programme (UNDP), Australia, Belgia, Inggris, Kanada Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, Austria, dan Amerika Serikat (Arumdanie, 2018: 128-129).
Walau IGGI di gambarkan sebagai upaya mulia Soeharto untuk petani Indonesia tetapi sejatihnya adalah asal muasal dari upaya proletarisasi massal di Indonesia karena mempengaruhi sektor nasional lainnya. Kita bisa lihat bagaimana IGGI turut memberikan pembiayaan dan nasehat pada program transmigrasi di Papua 1986 (Auparay, 2012: 21). Dimana program transmigrasi memberikan kontribusi kepada pembukaan lahan besar-besaran, pembukaan lahan kelapa sawit, pembukaan lahan untuk Food Estate, dan menciptakan tenaga kerja murah. Pada konteks Indonesia kini, Omnibuslaw Cipta Kerja menjadi pintu untuk mengsinkronkan berbagai prodak undang-undang untuk memuluskan kepentingan kapitalisme.
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu jerat kapitalis, di mana petani dan masyarakat adat yang sejak awal posisinya dilemahkan kemudian diiming-imingi dengan kepemilikan lahan melalui reforma agraria. Berbagai produk hukum lahir bahkan beberapa kementerian dilebur menjadi satu diera Jokowi, salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Transformasi sektor kehutanan lewat UUCK pasal 29A dan 29B dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada BAB VI Pasal 2023-247, menjadi dasar hukum penyelenggaraan program Perhutanan Sosial oleh Menteri LHK lewat Permen LHK No 9 Tahun 2021. Dimana program Perhutanan Sosial melalui 5 skema[5] diimplementasikan dengan kerangka nasional lewat penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan dan kemitraan lingkungan.
Empat dari 5 skema ini dijalakan dikawasan hutan negara dengan fungsi konservasi, lindung dan produksi, sementara ada pengecualian dalam skema Hutan Adat. Disini bukan lagi inkonsistensi tapi strategi melembagakan tanah adat dikotomi pemberian akses legal dan pengakuan lewat persetujuan (untuk 4 skema lainnya) dan penetapan (untuk HA) SK oleh Menteri.
Para petani kecil dan masyarakat adat digiring ke dalam masyarakat pra industry. Hal ini terlihat jelas bagaimana peran KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) yang berada di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak dalam penyelengaraan manajemen pengelolaan kehutanan ditingkat tapak, yang dulunya bisa berusaha artinya jadi pelaku usaha kini beralih peran dari pelaku usaha menjadi fasilitator bagi Kelompok Tani dan Masyarakat yang adat diwilayahnya. Istilah “No KPH, No Budget” kinipun beralih menjadi “KPH Efektif” sebagai ukuran kinerja untuk suntikan dana pengelolaan kawasan hutan.
Sementara melalui skema PS (Perhutan Sosial) yang notabene diarahkan pada fungsi kawasan yang sama dengan KPH, bahkan PIAPS (Peta indikatif areal perhutanan Sosial) untuk usulan PS baik dari Individu, Kelompok Tani atau Koperasi dan badan hukun lainnya telah ditetapkan oleh Menteri sebagai target capaian. Maka tidak menuntut kemungkinan invetarisasi potensi Hasil Hutan Kayu, Bukan Kayu dan Jasa lingkungan, pasca pemberian SK Ijin atau Persetujuan oleh Menteri hanya akan menjadi dasar bagi investor untuk meraup keuntungan besar termasuk mendapatkan pekerja dengan upah murah karena berlindung dibalik program Perhutanan Sosial yang SK nya di mata hukum setara dengan konsensi perusahaan.
Pada konteks Tanah Papua, persetujuan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan penetapan Hutan Adat yang berbatas waktu ini, setelah masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang maka akan jatuh ketangan siapa hak penguasaan hutan tersebut, kepada negara ataukah negara ke Investor? Inilah jeratan kapitalisme dalam rangka memonopoli asset dan sumber-sumber produksi di Tanah Papua.
Referensi
Auparay, max (2012) EKonomi Politik Migrasi Penduduk Papua, Jayapura: CV. Praja mandiri
Berstein, Henry (2020) Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, Edisi Revisi: Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria, Sleman: Insist Press
Bosko, Rafael E. (2006) Hak-hak Masyarakat adat dalam konteks pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: ELSAM
Elcid Li D dan Sujarwoto (2021) Ketidakadilan Sosial Kapitalisme dan Demokrasi: Catatan dari Penjuru Indonesia Tahun 2021: Indonesia Sosiall Justice Network
Fukuyama, Francis (2004) The End Of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Dempkrasi Liberal, Yohyakarta: Penerbit Kalam.
Mulyanto, Dede (2012) Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik pranata eksploitasi Kapitalistik, Yogyakarta: Resist Book.
Murray, Tania L (2020) Kisah dari Kebun Teakhir: Hubungan Kapitalis di wilayah adat, Serpong Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri.
****
[1] Undang-undang yang dikeluarkan dalam rangka mengakhiri hak-hak tradisional atas tanah
[2] Undang-undang reformasi
[3] Saya menulis dan sedikit memmbahasnya di: https://laolao-papua.com/2021/08/14/masyarakat-adat-dan-marxisme-kritik-terhadap-lembaga-adat-kolonial-di-papua/
[4] Pada konteks Papua, Masyarakat adat Papua di perkirakan telah berada sejak 50.000 tahun yang lalu dengan ras utama adalah Papua, Negrito, dan Melanesia (Osboner, 2001: 1). Dengan memiliki sekitar 253 kelompok bahasa, masing-masing kelompok memiliki tradisi, konsep agama, struktur social dan mengingat ragam lingkungan geografis yang berbeda dan tentu saja ragam budaya material dan bentuk ekonomi (Zöllner, 2006)[4].
[5] 5 Skema Perhutanan Sosial : Hutan Desa,Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Dimana Arahan areal Pengelolaan PS ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial)